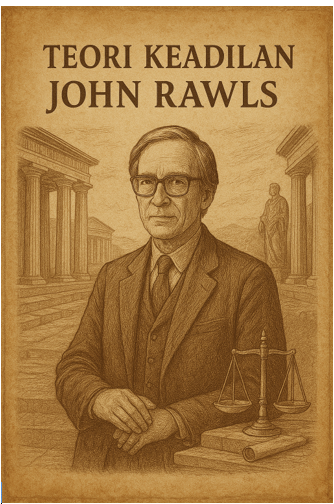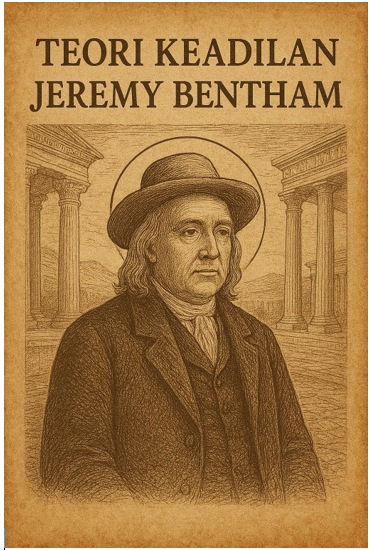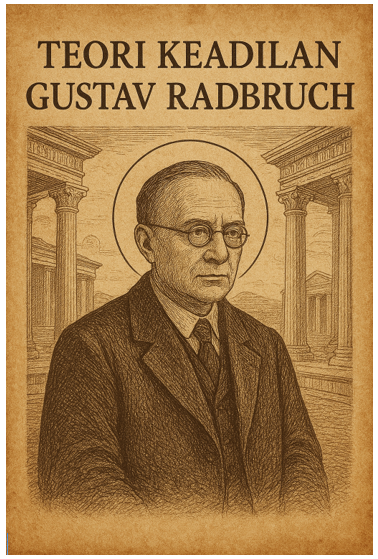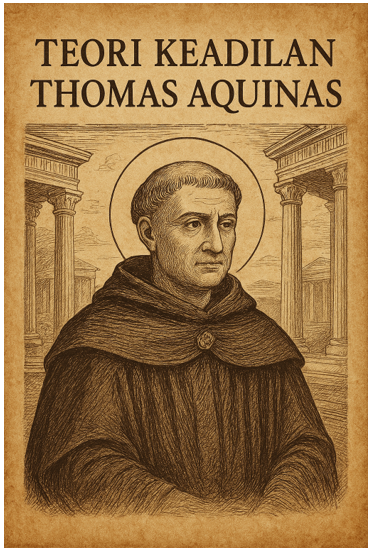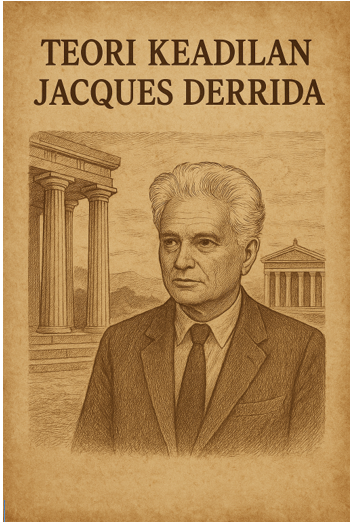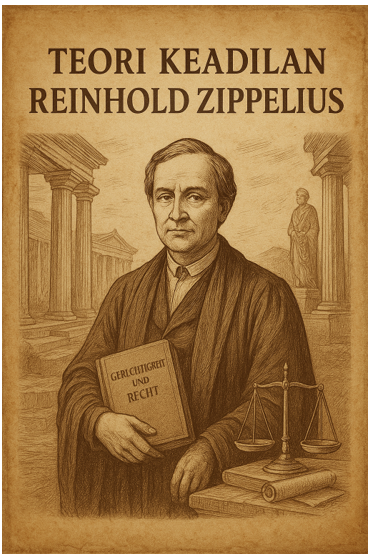
Teori Keadilan Menurut Reinhold Zippelius: Antara Norma Hukum dan Nilai Sosial dalam Dinamika Kehidupan
Wamena, Keadilan merupakan konsep yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat dan hukum. Salah satu pemikir yang memberikan warna baru terhadap teori keadilan modern adalah Reinhold Zippelius seorang filsuf hukum dan teoritikus asal Jerman yang dikenal melalui karyanya Rechtsphilosophie (Filsafat Hukum). Zippelius menolak pandangan bahwa keadilan bersifat statis dan mutlak. Ia justru melihat keadilan sebagai konsep yang hidup (lebendiges Recht), yang harus beradaptasi dengan perubahan nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat. Baca Juga : Teori Keadilan Menurut Plato: Harmoni Jiwa dan Negara dalam Filsafat Klasik Yunani Latar Belakang Pemikiran Reinhold Zippelius Reinhold Zippelius (lahir 1928) adalah profesor hukum di Universitas Erlangen-Nürnberg, Jerman. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam filsafat hukum kontemporer Jerman, yang mencoba memadukan antara pendekatan normatif, sosiologis, dan etis terhadap hukum. Zippelius hidup di masa pasca-Perang Dunia II periode ketika masyarakat Jerman mengalami krisis moral dan hukum, terutama akibat kehancuran hukum positif di masa Nazi. Dari konteks itu, Zippelius mengembangkan pandangan bahwa hukum dan keadilan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan dan dinamika sosial. Keadilan sebagai Orientasi Moral Hukum Bagi Zippelius, keadilan adalah orientasi moral dari sistem hukum. Hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan norma yang sah secara formal, tetapi juga harus mencerminkan cita-cita moral masyarakat. Menurutnya, keadilan adalah ukuran etis yang menilai apakah hukum positif benar-benar layak dipatuhi. Artinya, hukum yang adil bukan sekadar hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang, melainkan hukum yang sesuai dengan prinsip moral universal dan kemanusiaan. “Keadilan bukanlah produk logika hukum, tetapi hasil refleksi moral manusia yang hidup di dalam masyarakat.” – Reinhold Zippelius, Rechtsphilosophie. Hukum yang Hidup (Lebendiges Recht) Salah satu gagasan utama Zippelius adalah konsep “hukum yang hidup” (lebendiges Recht). Menurutnya, hukum bukan sekadar sistem aturan tertulis, melainkan juga praktik sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, keadilan juga bersifat dinamis ia berubah mengikuti perubahan kesadaran sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Contohnya, prinsip keadilan di masa feodal (yang mengakui hierarki sosial) tentu berbeda dengan keadilan di era demokrasi modern (yang menuntut kesetaraan hak). Keadilan dan Rasionalitas dalam Penegakan Hukum Zippelius menekankan bahwa keadilan hanya bisa diwujudkan jika hukum ditegakkan secara rasional dan komunikatif. Ia menolak pandangan positivistik yang melihat hukum sebagai sistem tertutup dan kaku. Sebaliknya, menurut Zippelius, hukum harus terbuka terhadap kritik moral dan sosial, karena hanya dengan begitu hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Keadilan yang sejati menurutnya melibatkan: Rasionalitas hukum — hukum harus logis, konsisten, dan dapat dipahami oleh publik. Komunikasi sosial — hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Keterbukaan moral — hukum harus dapat dikritik jika melanggar prinsip kemanusiaan. Keadilan dan Dinamika Sosial Zippelius berpandangan bahwa keadilan bukanlah hasil akhir, tetapi proses yang berkelanjutan. Proses ini terjadi melalui interaksi antara hukum, moral, dan masyarakat, di mana setiap generasi berhak menafsirkan kembali makna keadilan sesuai dengan tantangan zamannya. Dalam konteks modern, misalnya, keadilan kini mencakup isu-isu baru seperti: Hak digital dan privasi, Keadilan lingkungan (environmental justice), Keadilan gender dan kesetaraan sosial, Hak minoritas dan kelompok rentan. Zippelius menegaskan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Relevansi Pemikiran Zippelius Saat Ini Dalam konteks Indonesia, gagasan Zippelius tentang hukum yang hidup dan keadilan yang dinamis sangat relevan. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep “hukum yang hidup di masyarakat” (living law) yang diakui dalam sistem hukum nasional. Misalnya, penerapan hukum adat, penyelesaian sengketa sosial berbasis musyawarah, dan pendekatan keadilan restoratif merupakan wujud nyata dari pandangan Zippelius bahwa hukum harus berakar pada kehidupan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. (Gholib) Referensi: Zippelius, Reinhold. Rechtsphilosophie. München: C.H. Beck Verlag, 1999. Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Harvard University Press, 1945. Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971. Fuller, Lon L. The Morality of Law. Yale University Press, 1964.